BPJS Kesehatan: Nasib korban kekerasan seksual saat BPJS tak menanggung layanan kesehatan


Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images
-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
Waktu membaca: 15 menit
Para korban kekerasan domestik dan seksual memikul beban berat sejak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) tidak lagi menanggung pelayanan kesehatan korban kekerasan seksual.
Belum lama ini, pendamping hukum dari Women Crisis Center Perempuan Nusantara (WCC Puantara), Siti Mazuma, mengurus korban anak yang mengalami kasus kekerasan seksual. Pelaku adalah ayah si anak.
Sang ibu, dengan pendapatan tak seberapa, mesti bekerja ekstra keras untuk mengumpulkan uang demi pengobatan psikologis anaknya. Jadwal berkunjung ke psikiater, menurut Siti, ialah sebulan sekali.
Siti mengatakan biaya pemulihan psikis tidaklah murah. Itu membikin ibu korban berupaya mencari peluang tambahan pemasukan ke bermacam pintu.
Pada kesempatan terpisah, dengan jarak waktu yang berdekatan, Siti mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Korban, yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu, diharuskan membayar visum secara mandiri apabila hendak membawa kasusnya ke ranah hukum.
Menurut Siti, korban tidak punya cukup uang.
“Kami bersama-sama teman jaringan kemudian patungan untuk membayar visum ini,” tandas Siti saat diwawancarai BBC News Indonesia, Senin (9/2).

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Jalan pemulihan bagi korban kekerasan perempuan dan anak, dalam beberapa waktu belakangan, sangat tajam nan berliku, ungkap Siti.
Sebelum ramai urusan pencabutan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berdampak terhadap 11 juta pengguna, negara lebih dulu berlaku tidak adil kepada perempuan serta anak korban kekerasan—baik domestik maupun seksual, menurut Siti.
“Kalau di sini kemudian korban harus membayar biaya visum dan semacamnya, padahal dia sudah berstatus korban, maka negara mengabaikan kewajibannya,” tegas Siti.
‘Pembuktian selalu dibebankan kepada para korban’
Siti menerangkan sebelum 2024, pembiayaan pemulihan korban kekerasan ditanggung oleh BPJS Kesehatan—mulai dari pembuatan visum hingga layanan psikologis.
Pernah satu waktu Siti mendampingi korban kekerasan seksual. Korban tersebut hamil dan kemudian melahirkan. Sejak mula, korban tak perlu merogoh kocek untuk berbagai kebutuhan, tinggal menyerahkan kartu BPJS Kesehatan. Semuanya ditanggung.
“Jadi, layanan kesehatan itu secara kontinu menyediakan kebutuhan untuk para korban (kekerasan), bahkan termasuk perawatan anak yang dia lahirkan tadi. Dan untuk tenaga kesehatannya sendiri pun sudah tahu bagaimana melakukannya (pendampingan) karena mereka dibekali pedoman yang sangat mendukung korban,” papar Siti.
Dalam aturan itu, tepatnya Pasal 52 (1), dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan akibat “tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang” dikecualikan dari jaminan kesehatan.
Masih pada pasal yang sama, pihak yang bertanggung jawab untuk membiayai pelayanan kesehatan korban-korban dengan kriteria tersebut yakni “kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah” menggunakan “skema pendanaan lain” serta “sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Siti menyebut kondisi yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan usai peraturan itu disahkan “sangat pelik.”
Pendampingan yang ditempuh Siti kerap kali membutuhkan pemenuhan atas visum, baik yang sifatnya visum et repertum atau visum psikiatrikum. Yang pertama dipakai untuk mencatat bukti kekerasan fisik, yang kedua menyasar kekerasan mental—psikis.
Ongkos keduanya, menurut Siti, “tidak murah.”
Pada 2025, sekali visum et repertum, misalnya, pendamping hukum dari korban kekerasan harus mengeluarkan dana sekira Rp500 ribu.
“Dan itu di rumah sakit di Jakarta. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana situasi teman-teman di daerah yang kesulitan akses layanan fasilitas kesehatan untuk bisa visum,” tutur Siti.
Siti berpandangan keberadaan visum amat krusial dalam rangka mencari keadilan hukum kepada para korban kekerasan. Visum, Siti menggaris bawahi, “dapat menjadi bukti penguat” bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik—begitu pula trauma yang ditimbulkan.
“Nah, (kekerasan) itu kemudian bisa tergambarkan dan membantu penyidik untuk memprosesnya secara hukum,” tambahnya.
Sebagai pendamping korban, Siti memprioritaskan kepentingan korban di atas segalanya. Dengan kata lain, Siti, dan organisasinya, akan “berusaha maksimal” agar visum tetap di tangan tanpa memaksa korban untuk mengeluarkan biaya sendiri.
Untuk itu, para pendamping “bekerja keras memutar otaknya” demi menutup pengeluaran terhadap visum.

Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Langkah pertama yang Siti ambil, biasanya, disandarkan ke instansi pemerintah yang masih menggratiskan visum seperti Rumah Sakit (RS) Polri atau fasilitas kesehatan di tingkat daerah yang berpedoman pada aturan internal mereka terkait biaya penyertaan visum.
Jika strategi tersebut buntu, Siti pindah ke kesempatan berikutnya: pengajuan anggaran serta pengumpulan dana (public fundraising).
Pengajuan anggaran ditujukan kepada organisasi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu perlindungan anak serta perempuan.
Sedangkan untuk donasi publik, kerja sama dengan pihak lain adalah jalan keluarnya.
Dalam perspektif Siti, penggalangan dana secara terbuka merupakan “bentuk dukungan yang penting” supaya “korban tidak merasa sendirian.”
“Karena ketika negara tidak mampu membiayai korban, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan, maka kita akan melakukan kampanye di publik. Ini wujud solidaritas. Penanganan kekerasan tidak cuma jadi tanggung jawab satu kelompok saja,” terangnya.
Lantas bagaimana dengan mekanisme pembiayaan oleh “instansi lain” seperti yang tertuang dalam Perpres 59?
Siti menjawab kemungkinan itu tidak seketika tertutup, walaupun tidak semua korban memilih solusi demikian.
Bicara konteks “lembaga negara yang lain” dalam skema pembiayaan pemulihan atas perempuan dan anak korban kekerasan, berdiri nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK, Siti bilang, bisa mengganti uang untuk visum selama pihak bersangkutan mengajukan reimbursement.
Persoalannya, gerak instansi pemerintah, kini, terbatas.
“Pada akhirnya untuk akses keadilan, justice, selama ini pembuktian itu selalu dibebankan kepada korban,” ujar Siti.
‘Dikembalikan saja ke JKN’
Dikeluarkannya ketentuan pelayanan kesehatan akibat tindak kekerasan—domestik dan seksual—dari Jaminan Kesehatan Negara (JKN) diakui Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, mengubah peta yang ada.
Saat JKN tidak menjamin biaya pemulihan korban kekerasan seksual dan domestik, peran tersebut dipanggul oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Meski demikian, masalah tidak otomatis lenyap.
LPSK, Timboel menjelaskan, hanya akan menjamin biaya tanggungan visum—ambil contoh—andaikata terdapat laporan ke kepolisian.
“Supaya bisa dijamin oleh pemerintah, korban mesti melaporkan secara resmi. Maka dengan itu, LPSK akan melakukan kaitan dengan polisi. Polisi akan memproses. Pelaku, atau suami, lalu dipanggil. Nah, baru dari situ bisa dijamin,” papar Timboel kala dihubungi BBC News Indonesia, Minggu (8/2).
Sebaliknya, ketika korban tidak berkenan untuk membuat laporan resmi, LPSK pun tidak bergerak. Ketidakmauan korban dalam melaporkan pelaku kerap dipicu kenyataan bahwa pelaku masih berhubungan dekat dengan korban—satu lingkaran. Pelaku bisa jadi adalah suami atau ayah sendiri.
Artinya, biaya penanggulangan kekerasan “yang menjamin yaitu diri sendiri,” tegas Timboel.
“Jadi dilema buat korban,” imbuh Timboel.

Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images
Sebelumnya, tatkala JKN—BPJS—masih menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan akibat tindak kekerasan, korban “tinggal datang ke rumah sakit untuk setelahnya dirawat,” jelas Timboel.
Perihal pelaku kekerasannya, “itu diurus secara terpisah,” Timboel menekankan.
“Kalau LPSK tidak begitu. Untuk menjamin, harus satu rangkaian dari awal, bahwa harus ada laporan secara resmi dan semacamnya,” ungkap Timboel.
Posisi LPSK, sebetulnya, tidak ideal. Kebijakan efisiensi yang dicetuskan pemerintahan Prabowo Subianto sejak pertama kali dilantik turut memotong anggaran yang diterima LPSK.
Pada 2025, alokasi anggaran yang disediakan untuk LPSK turun sebesar 17,45% ketimbang 2024. Per Desember 2025, pagu efektif LPSK berada di angka Rp220 miliar.
Pemandangan serupa muncul pada 2026. Anggaran LPSK semula ialah Rp259 miliar. Seiring waktu, LPSK diminta memangkas Rp63 miliar—atau 24,6% dari keseluruhan—sehingga tersisa Rp195 miliar.
Pemotongan anggaran tidak dimungkiri membuat LPSK terjepit dalam menuntaskan kerja-kerjanya. Sekretaris Jenderal LPSK, Sriyana, mengutarakan bahwa jangkauan LPSK terhadap saksi dan korban diperkirakan tidak maksimal.
“Bahkan kami harus menunggu tahun depan karena memang anggaran belum mencukupi,” kata Sriyana, awal Januari silam.
Yang menghadapi pemangkasan, dalam konteks penanggulangan perempuan dan anak korban kekerasan, tidak sekadar LPSK. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) setali tiga uang.
Pada 2025, Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, mengeluh dengan ketiadaan anggaran untuk program kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak di anggaran 2026.
Pagu indikatif anggaran 2026 bagi Kementerian PPPA turun sebesar 55,74% dibanding 2025. Arifatul meminta adanya penambahan anggaran senilai Rp50 miliar.
“Usulan tambahan anggaran akan dimanfaatkan untuk kegiatan antara lain penyediaan layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,” papar Arifatul.
Terbatasnya anggaran memicu ketidakleluasaan Kementerian PPA dalam mendampingi korban kekerasan, aku Arifatul. Dia mencontohkan beberapa kasus di Yogyakarta serta Jawa Barat yang dianggapnya “memprihatinkan” sebab kementerian tidak mampu berbuat banyak imbas kendala penggunaan dana.
Di Yogyakarta, seorang korban kekerasan oleh pasangan memerlukan dana untuk bolak-balik ke rumah sakit. Korban disiram air keras.
Lalu di Jawa Barat, keluarga perempuan korban kekerasan “masih berhutang” kepada rumah sakit setelah anak mereka mengalami kecelakaan dan dikeroyok.

Sumber gambar, Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images
Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti betapa pemotongan anggaran kementerian maupun lembaga yang mengurusi perlindungan perempuan dan anak “akan berdampak dalam upaya menurunkan kekerasan” yang menimpa mereka.
Pemangkasan anggaran, sebut Seknas FITRA, sama saja dengan mengurangi pencegahan terhadap tindak kekerasan dan membikin, pada akhirnya, “perempuan serta anak korban kekerasan terabaikan” dari proses perlindungan maupun pemulihan.
Menurut Timboel, pemerintah seharusnya mengembalikan klausul “korban kekerasan domestik (penganiayaan) dan seksual” ke dalam kategori yang ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pasalnya, Timboel berpendapat, JKN mempunyai “infrastruktur keuangan yang begitu besar” serta terdistribusi dari Sabang hingga Merauke—atau seluruh Indonesia.
Terlebih, tambah Timboel, penanganan korban kekerasan tidak selesai dalam sekali jalan. Para korban memerlukan pendampingan hingga pemulihan yang memakan waktu tidak sebentar supaya benar-benar “terbebas” dari kondisi sakit atau trauma.
“Nah, jangan lupakan pula bahwa tidak jarang korban kekerasan itu memiliki penyakit lainnya yang ditimbulkan dari tindak kekerasan itu sendiri,” terang Timboel.
“Sebaiknya memang dikembalikan ke JKN karena pada intinya masyarakat itu diberi akses yang mudah saja.”
Pesan dari daerah: anggaran jangan dipangkas
Cakupan BPJS Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan domestik maupun seksual dipandang tidak menyeluruh, merujuk keterangan anggota Samahita Foundation, organisasi yang fokus dalam isu kekerasan seksual, Talissa Febra.
Terbatas lantaran BPJS, menurut Talissa, bekerja dalam bingkai kasus atau kondisi yang bersifat kuratif—pengobatan.
Apabila digunakan untuk mengobati kondisi kesehatan pasien korban kekerasan, seperti luka pukul, fisik akibat pemerkosaan, sampai trauma psikologis, BPJS dapat menanggung biayanya.
Begitu masuk ke ranah hukum atau forensik, “yang fokusnya untuk mengumpulkan bukti dalam proses pidana,” Talissa meneruskan, maka tidak bisa diklaim BPJS Kesehatan. Bukti yang dimaksud meliputi visum et repertum, dokumentasi luka detail, hingga pemeriksaan cairan atau sampel tubuh.
“Sehingga sering kali tidak bisa diklaim ke BPJS, dan biaya bisa dibebankan ke pasien jika tidak ada penjamin,” ucap Talissa kepada BBC News Indonesia, Senin (9/2).
“Yang menjadi masalah adalah korban butuh dua-duanya, untuk pengobatan dan forensik, tapi karena sistemnya terpisah, ini akhirnya memberatkan bagi korban.”
Berdasarkan pengalaman Samahita Foundation mendampingi para korban kekerasan, biaya untuk penanganan maupun pemulihan dibayar oleh lembaga bersangkutan. Ini tak lepas dari kondisi ekonomi para korban yang terbatas. Banyak korban yang belum terdaftar BPJS Kesehatan atau kepesertaannya nonaktif karena tunggakan iuran, cerita Talissa.
Bicara penanganan kekerasan domestik dan seksual tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, Talissa menjelaskan. Semua pihak punya peran yang sama pentingnya untuk menjamin keberlanjutan nasib para korban.
Semua pihak di sini tidak terkecuali pemerintah. Tapi, bagaimana jadinya kalau kebijakan yang dikeluarkan justru menjauhkan para korban dari pemulihan yang layak?

Sumber gambar, Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images
Awal Januari lalu, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Sumbawa, Fatriatulrahma, menyatakan bahwa biaya visum, per 2026, tidak lagi ditanggung pemerintah daerah.
Dengan biaya visum tidak ditalangi, banyak korban yang berasal dari golongan tidak mampu secara ekonomi menjadi kesulitan dalam mencari keadilan.
Posisi korban yang “sudah menjadi korban” seharusnya tidak lagi dibebani dengan urusan pembiayaan terhadap bermacam aspek pemulihan, papar Direktur YLBH Apik, Uli Pangaribuan.
Negara wajib menyediakan akses sebebas serta seluas mungkin dalam konteks perlindungan kepada para perempuan dan anak korban kekerasan.
“Korban itu banyak dari kelompok yang ekonominya susah. Ketika negara tidak memberikan layanan yang gratis kepada korban, maka mereka mencabut tanggung jawabnya sebagai pemegang otoritas,” tandas Uli kepada BBC News Indonesia, Senin (9/2).
Di Jakarta, Uli mencontohkan, pembuatan visum et repertum sama sekali tidak dikenakan biaya. Selama korban memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta atau kejadian kekerasan berlokasi di Jakarta, korban dapat memperoleh visum.
Namun, Uli menjelaskan tidak semua daerah menerapkan aturan sejenis, dan ini cukup mengkhawatirkan.
Bagaimanapun, Uli melanjutkan, pemenuhan visum merupakan “kebutuhan dasar” setiap korban yang mesti dijamin negara.
Kemungkinan terburuk dari pematokan biaya atas visum yaitu korban tidak mau melaporkan kekerasan yang dialaminya. Konsekuensinya: kasus kekerasan bertambah serta korban akan menjadi korban lagi.
Uli mendefinisikannya sebagai “siklus setan yang berulang.”
“Kami pernah mendampingi beberapa korban, dan ketika korban mengetahui visum berbayar, mereka tidak jadi membuatnya. Karena lebih baik uangnya dipakai untuk keperluan yang lain,” ucap Uli.
Riset yang disusun YLBH Apik menunjukkan korban kekerasan domestik maupun seksual hampir selalu terganjal urusan finansial.
“Luka fisik dan psikis berdampak lebih lanjut terhadap aspek ekonomi dan pekerjaan. Mengenai yang terakhir, korban harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk biaya pengobatan,” tulis YLBH Apik.
Sementara di lain sisi, merujuk data yang dikumpulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan perempuan serta anak dalam rentang Januari-Oktober 2025 menyentuh lebih dari 25.180 dengan 26.861 di antaranya menjadi korban.
Dari jumlah itu, setengahnya (14.795 kasus) muncul di lingkungan rumah tangga, melibatkan orang-orang terdekat. Alhasil, “korban merasa terjebak dan sulit mencari pertolongan,” ungkap Kementerian PPPA.
Dari sekian bentuk kekerasan, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dalam catatannya, pernah menggambarkan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan (36,43%), disusul setelahnya kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%), dan kekerasan ekonomi (9,84%).
Uli melihat kebijakan-kebijakan yang dicetuskan negara dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak masih jauh dari kata maksimal. Bahkan, “tidak berpihak terhadap korban,” Uli menegaskan.
Uli memberi contoh dengan pemangkasan anggaran kementerian maupun lembaga, di samping yang terbaru: pembatalan BPJS Kesehatan jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang berefek ke belasan juta masyarakat—terutama dari kelompok miskin.
“Ini menandakan pemerintah seperti memandang bahwa kasus-kasus kekerasan tidak perlu diselesaikan,” ujarnya.
Kementerian PPA tengah memastikan pihaknya tak luput dalam menjaga kelancaran penanggulangan kekerasan berbasis gender. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, meminta pemerintah daerah memanfaatkan distribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk, salah satunya, penyediaan visum tak berbayar.
Sejauh ini, negara, secara hitam di atas putih, telah mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan melalui, misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Untuk itu, negara “harus hadir dalam pemenuhan keadilan dengan penegakan hukum,” menurut Talissa.
Jangan sampai, Talissa mengingatkan, perempuan korban kekerasan semakin terjerumus saat berusaha mencari kepastian dari otoritas yang sebenarnya memiliki kewenangan luas untuk menjalankan perlindungan.
‘Korban menangis ketika dapat pelayanan psikologis’
Masih terekam dengan jelas bagaimana korban kekerasan domestik yang didampingi Velmariri Bambari menangis kencang sehabis berbincang bersama seorang psikolog.
Korban, merujuk cerita Velmariri, bertahun-tahun menjadi korban kekerasan. Tak sebatas fisik, melainkan psikis. Pelaku kekerasan yakni suaminya sendiri.
Velmariri lantas memutuskan untuk mendampingi korban. Salah satu hal yang dia upayakan adalah korban mendapatkan layanan konseling atau psikologis.
Di tempat tinggalnya, Lembah Bada, Sulawesi Tengah, ketersediaan pelayanan psikis tidak ada. Velmariri mesti membawa korban ke Kota Poso yang berjarak sekira 145 kilometer dari lokasinya bermukim, atau kurang lebih 4 hingga 5 jam perjalanan darat.
Berangkatlah Velmariri dan korban ke Kota Poso. Di sana, psikolog sudah menanti. Sesi antara korban dengan psikolog pun dilangsungkan.
Velmariri mengingat pertemuan korban serta psikolog berjalan cukup lama. Selesai sesi, korban menghampiri Velmariri serta berkata bahwa dirinya telah lega.
“Dia (korban) sampai menangis di sesi itu,” Velmariri memberi tahu BBC News Indonesia, Minggu (8/2).
“Saya sangat bersyukur dan sekarang dia sudah perlahan pulih.”
Sepanjang berkecimpung dalam dunia pendampingan korban kekerasan, Velmariri senantiasa menekankan pentingnya tentang agensi korban. Velmariri tidak mau korban kembali ke pelukan pelaku—suami—dan kemudian mengalami lagi tindak kekerasan.
Di sinilah, Velmariri bilang, pelayanan psikologis mengambil tugas. Velmariri bukan ahli, dan sebab itu dia membutuhkan uluran tangan dari profesional.
Permasalahannya, akses ke ruang-ruang bantuan psikologis tidaklah gampang diraih. Selain faktor jarak, yang mana Velmariri harus berkendara berjam-jam ke kota untuk sekali sesi, biaya konseling juga dia rogoh dari kantong organisasi tempatnya bekerja.
Dan itu “tidak murah,” papar Velmariri tanpa merinci berapa uang yang dia keluarkan untuk mengakomodasi perjalanan.
Dalam kaitannya dengan pemulihan korban kekerasan, kondisi di daerah, seperti tempat tinggal Velmariri, “sangat terjerat.” Alasannya tak lain dan tak bukan: terbatasnya anggaran.
Di luar perkara konseling psikis, sejumlah hambatan kerap Velmariri jumpai tatkala mendampingi para korban.
Biaya mengurus persidangan, termasuk di dalamnya merangkap transportasi, ambil contoh, dibebankan kepada para korban. Padahal, rata-rata korban yang ditemani Velmariri bukan berasal dari kelompok ekonomi mampu.
“Polisi, misalnya, hanya mengubungi kami bahwa dipanggil untuk pemeriksaan atau yang lain-lain. Tapi, untuk akomodasi, makan dan perjalanan ke pengadilan, yang mana juga jauh dari rumah kami, itu kami yang tanggung,” aku Velmariri.
Baru-baru ini pula Velmariri menghadapi situasi yang tak menguntungkan. Ketika meminta polisi untuk mencari pelaku kekerasan yang lari dari kampung halaman, respons yang dia terima adalah “kami tidak bisa ke mana-mana (mencari) karena ada penyesuaian anggaran operasional.”
Velmariri berharap keleluasaan dalam menangani para korban kekerasan berbasis gender tidak ditebas, meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Karena, pada dasarnya, kejahatan yang diarahkan ke perempuan—serta anak—yang mewujud lewat kekerasan domestik maupun seksual, berdampak hebat dalam keberlangsungan masyarakat, Velmariri meyakinkan.

Sumber gambar, Evan Praditya/INA Photo Agency/Universal Images Group via Getty Images
Senada, pendamping hukum dari Women Crisis Center Perempuan Nusantara (WCC Puantara), Siti Mazuma, menyatakan bahwa negara—sebetulnya—punya “banyak skenario” pendanaan yang dapat direalisasikan.
Siti menyodorkan opsi penganggaran dengan skema “alokasi khusus” bagi para korban kekerasan. Alokasi ini nantinya bisa dimanfaatkan dalam pemenuhan layanan fisik maupun psikis untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
Menjamin para korban memperoleh akses pemulihan adalah “tanggung jawab negara,” tegas Siti.
Sekarang yang jadi pertanyaannya ialah seberapa tinggi komitmen pemerintah dalam memastikan nasib para korban kekerasan?
“Kalau kemudian negara bisa membuat program yang lain dengan mengeluarkan uang triliunan rupiah begitu mudah, kenapa buat korban tidak mau?” pungkas Siti.




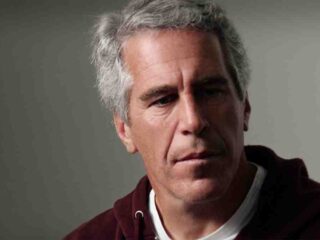






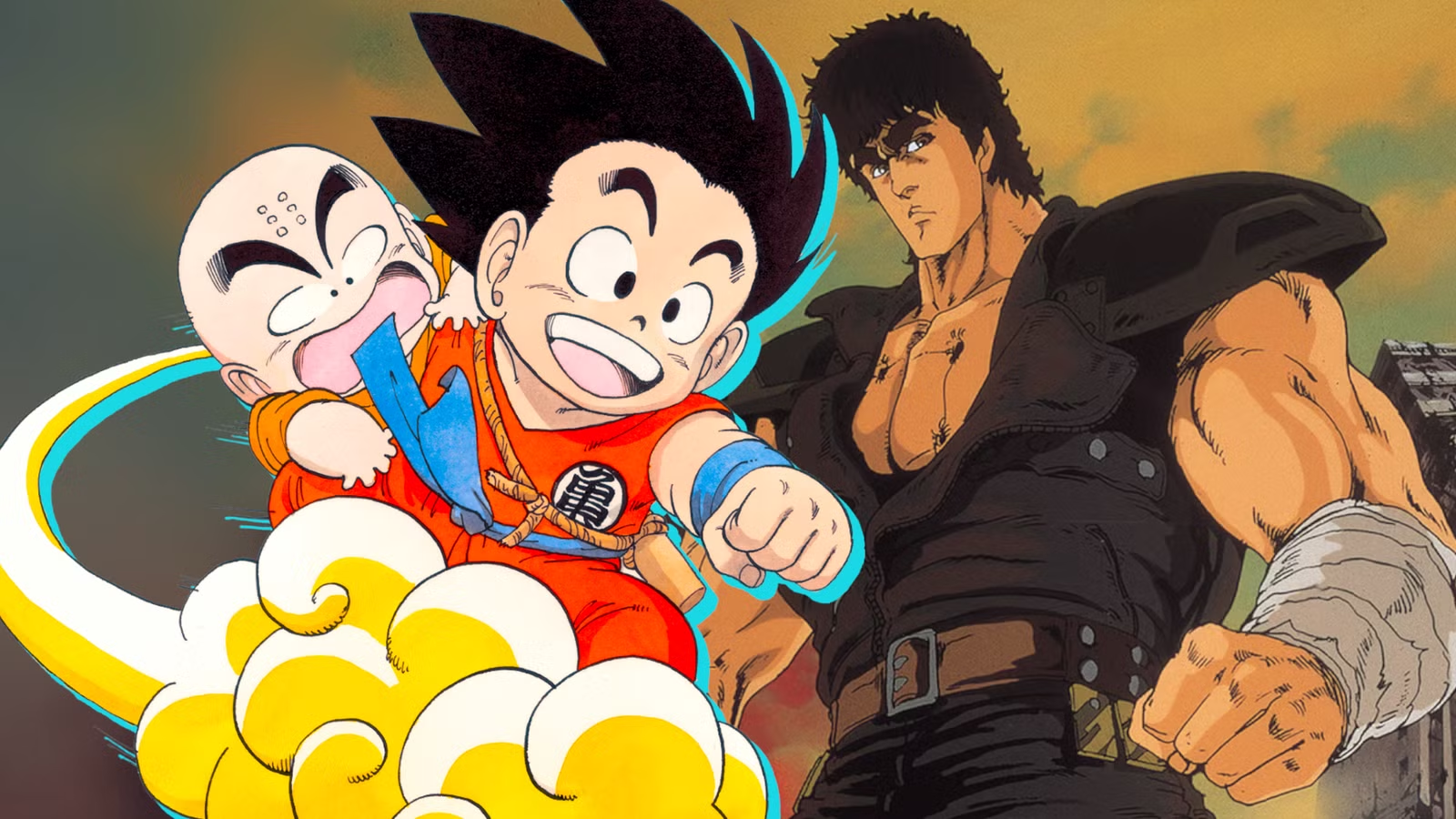





No Comments